Seperti Seorang Tukang Batu Menghantam Tembok
PERGOLAKAN PEMIKIRAN ISLAM Catatan Harian Ahmad Wahib Penyunting: Djohan Effendi dan Ismed Natsir. Dengan kata pengantar Prof. Dr. A. MuktiAli. LP3ES, Jakarta, 1981, 351 hal., tanpa indeks
Seorang Muslim yang meragukan Tuhan justru untuk lebih meyakini kehadiranNya. Itulah kesan dari catatan harian Ahmad Wahib, pemikir muda Islam yang meninggal tertabrak motor di depan kantor TEMPO dulu – kantor tempatnya bekerja sebagai reporter.
BAGI pembaca yang tidak mengenalnya secara pribadi, sulit mendapatkan kesan utuh tentang diri Ahmad Wahib hanya dari bukunya ini. Pemikir muda muslim yang mati muda ini (1943-1973), menyajikan dalam catatan harian yang diwariskannya, beberapa kepingan yang mungkin dapat menyajikan gambaran lengkap tentang kepribadian yang bulat, hanya setelah pengenalan pribadi yang cukup lama.
Ketulusan untuk memperoleh kebenaran dengan pertaruhan tertinggi. Keberanian menghadapkan diri sendiri kepada masalah-masalah keimanan terdalam – yang berarti pengakuan penuh atas keraguan mendasar dalam hati sendiri. Dan kemampuan untuk memetik pelajaran dari pihak mana pun. Semua itu adalah hal-hal yang saling bertentangan tetapi berkembang dalam hidup Ahmad Wahib.
Mengejar kebenaran secara tuntas mengandaikan kepastian sikap yang penuh – katakanlah semacam elan vitalnya seorang filosof. Sedangkan introspeksi ke dalam, justru menampakkan wajah yang berkebalikan. Lalu bagaimana pula keduanya harus dipertalikan dengan kelemahan hati seorang yang mampu belajar dari siapa pun?
Sulit diketahui 'bagaimananya' pergolakan pemikiran Ahmad Wahib. Terlebih-lebih kalau diteropong dari sisi lain watak hidupnya sendiri: kebimbangan (atau justru rasa rendah dirinya?) untuk mewujudkan tindak lanjut bagi ikatan kasih yang dijalinnya dengan seorang gadis, umpamanya. Atau sifat pemalunya yang demikian besar.
Kesan tiadanya keutuhan gambaran itulah yang muncul dari membaca buku ini. Padahal pribadi yang digambarkan justru sangat kuat proyeksinya kepada pembaca sebagai sesuatu yang utuh! Hanya orang tidak tahu keseluruhan wajah keutuhan itu sendiri.
Di sinilah harus disayangkan kegagalan kata pengantar Prof. Dr. A. Mukti Ali dan pendahuluan Djohan Effendi. Sebagai bekas pembimbing intelektual-keagamaan dan kawan terdekat Ahmad Wahib, seharusnya kedua orang tersebut menjelaskan secara terperinci aspek-aspek pergulatannya yang tidak tertangkap oleh orang lain. Manakah gambaran jelas tentang bermulanya proses itu? Dera apakah yang harus dijalani Ahmad Wahib dalam hidupnya, yang membentuk kepribadiannya? Sejauh manakah pemikir muda ini disengsarakan kejujurannya yang demikian mutlak itu?
Kita tahu ia harus bergulat, tetapi apa lingkup pergulatannya, kesakitannya sewaktu menjalani proses tersebut, harapan yang dirumuskannya sebagai ujung pergulatan?
Tetapi yang luar biasa dari buku ini adalah kenyataan akan tingginya intenitas pergulatan pemikiran dalam diri Ahmad Wahib. Tanpa ada kejelasan situasinya sekalipun, kita tetap merasakan betapa besar arti pergulatan itu bagi diri Ahmad Wahib sendiri dan bagi temanteman sejawatnya. Bahkan mungkin bagi perkembangan Islam sendiri, di sini!
Begitu kuat keterlibatan Ahmad Wahib kepada penentuan masa depan agama yang dicintainya itu, terasa bagi kita. Padahal, tetap saja tidak jelas apa visinya akan masa lampau agama tersebut. Kalau ia dapati kekurangan sedemikian mendasar di dalamnya, mengapakah Ahmad Wahib tidak menolaknya? Bahkan, sebaliknya, ia lebih dalam mencintainya – bagaikan orang mencintai pelacur walaupun tahu apa yang dilakukan pelacur itu sehari-hari.
Berpikir Nisbi
Dalam pernyataannya bahwa ia harus meragukan adanya Tuhan untuk dapat lebih merasakan makna kehadiran-Nya (hal. 23, 30 dan 47, umpamanya), jelas menunjukkan kebutuhannya sendiri kepada Tuhan yang itu-itu juga – bukannya Tuhan yang lain hasil 'buatannya' sendiri. Inilah yang merupakan inti kehadiran Ahmad Wahib dalam kehidupan kaum muslimin kita di permulaan tahun tujuhpuluhan: ketundukannya yang penuh kepada Yang Mutlak, dengan menggunakan cara-cara berpikir nisbi.
Selebihnya menarik terutama sebagai kesaksian historis akan potensinya yang besar di bidang pemikiran keagamaan seandainya ia tidak mati begitu muda. Betapa ia mengerti hakikat 'kebidatan'nya NU, sambil tetap tidak mampu melepaskan diri dari belenggu kecintaan kepada HMI. Betapa pandainya ia memaki kawan seiring, karena kepengecutan mereka dalam menanggung konsekuensi logis pemikiran mereka. Tetapi sambil merasa ketakutan, bahwa ia akan menganiaya mereka dengan tuntutan-tuntutan terlalu berat. Dan betapa Ahmad Wahib mampu mengajukan begitu banyak pertanyaan fundamental kepada teman-teman seagamanya, padahal ia sendiri sangat kekurangan pengetahuan dasar tentang pemikiran keagamaan itu sendiri!
Ia menyadari bahwa keterlibatannya kepada 'pembaharuan Islam' justru muncul dari kenyataan begitu besarnya kemelut kehidupan kaum muslimin sendiri. Dengan kata lain, Ahmad Wahib sedalam-dalamnya menyadari bahwa hanya satu-dua orang saja yang akan mampu mengikutinya. Sisanya, tetap saja berada dalam kemelut mereka.
Toh ia tak juga mau meninggalkan upaya 'meningkatkan keimanan' mereka, meskipun ia tahu akan gagal total. Dilakukannya itu tidak lain karena kecintaannya kepada Islam yang 'apa adanya saja', sebagaimana tampak di pelupuk matanya. Upayanya memberontak tidak lain karena ketakutan akan irelevansi 'Islam apa adanya' itu bagi orang lain di kemudian hari, bukan bagi dirinya.
Ternyata, kalau dilihat dari sudut ini, Ahmad Wahib merupakan sisi lain dari mata uang yang sama: ketakutan akan erosi keimanan kaum muslimin di kemudian hari. Wajah satunya lagi, adalah kuatnya kecenderungan sementara lulusan dan jebolan disiplin ilmiah eksakta untuk mengajukan 'kebenaran' Islam secara formal.
Ahmad Wahib sendiri adalah dari kelompok 'jebolan eksakta', yang kemudian lari ke filsafat. Tetapi ia menolak formalisme seperti itu. Namun tetap saja ia melakukan kerja mengukuhkan kehadiran Islam, seperti 'kaum formalis' itu.
Mengukuhkan Agama
Memang, sedalam-dalamnya Ahmad Wahib adalah seorang muslim dengan keimanan penuh. Pemberontakan yang dilakukannya justru bertujuan mengukuhkan agama yang diyakininya itu. Bak tukang batu yang menghantamkan palunya ke tembok, untuk menguji kekuatan dan daya tahan tembok tersebut. Siapa dapat mengatakan menjadi 'muslim bergolak dan pemberontak' seperti Ahmad Wahib ini lebih rendah kadarnya dari 'kemusliman' mereka yang tidak pernah mempertanyakan kebenaran agama mereka sekali pun?
Kutipan berikut dari catatan harian Ahmad Wahib dengan tepat menggambarkan kesimpulan itu. "Aku bukan nasionalis, bukan katolik. Aku bukan budha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim. Aku ingin bahwa orang memandang dan menilaiku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia". (hal. 46). Alangkah mulianya pribadi Ahmad Wahib, dan alangkah sempurna kemuslimannya.
Abdurrahman Wahid
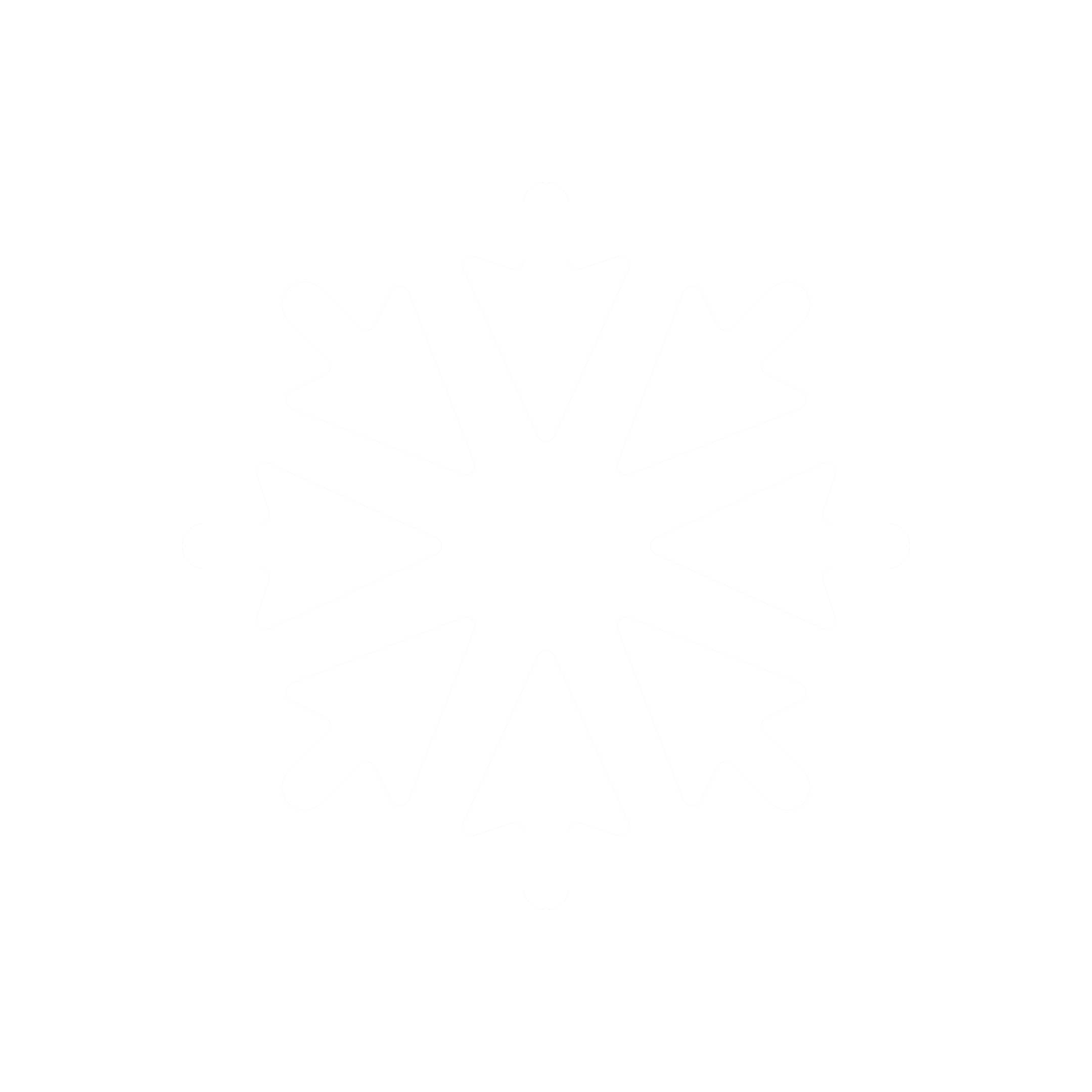
tiada manusia yang sempurna.
ReplyDelete